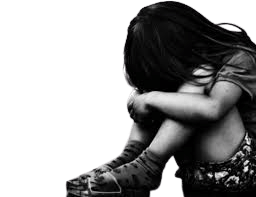Nama Kampus: Universitas Mulawarman
Prodi: Ilmu Pemerintahan 2022
Kelas: A
Kelomok 2:
Mela Feronika Siagian 2202026002
Muhammad Ilham 2202026009
Yosephin Satria Utami 2202026014
Jainah 2202026016
Salmah 2202026017
Jeni Arianda 2202026021
Puteri Najwani Rusyadah 2202026022
Adzkar Nawawi 2202026023
Alya Ramadhani 2202026031
Zherina Nur Fatihah 2202026036
Debby Amelyastuty Ami 2202026039
Nadya Amanda Syalsabila Hasim 2202026047
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Jürgen Habermas, seorang filsuf sosial yang memiliki pandangan mendalam tentang masyarakat sipil. Menurutnya, masyarakat sipil adalah ruang publik di mana warga negara dapat berdiskusi, berdebat, dan membentuk opini secara bebas. Ini adalah tempat di mana masyarakat sipil dapat mengawasi dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik.
Term “public sphere” atau ruang publik lahir dari karya Jurgen Habermas pada tahun 1989 melalui buku yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Gourgeois Society. Ruang publik tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu (private people) dalam konteks sebagai kalangan borjuis, yang diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. Hal ini muncul karena adanya perubahan kultur warga dalam menanggapi regulasi maupun realitas politik di abad ke-18; seiring dengan semakin intelektualnya warga, melek media, akses terhadap karya-karya bermutu, buku sastra yang mudah didapatkan, dan juga konsumsi terhadap arah baru jurnalisme yang lebih kritis melalui berita yang dipublikasikan. Juga, merupakan upaya untuk menyediakan ruang-ruang publik sebagai arena diskusi yang kritis (Räsonnement) berdasarkan argumen-argumen dalam menanggapi realitas atau pemberitaan media.
Meski ruang publik di abad tersebut Dikuasai oleh kalangan borjuis, banyak para Akademisi yang mengkritisinya, namun Habermas memunculkan apa yang disebutnya Sebagai “institutional criteria” (Habermas, 1962/1989:36). Sebuah karakter yang bisa Mengantarkan kita memahami apa yang dimaksud Habermas dengan ruang publik tersebut. Kriteria pertama adalah pengabaian terhadap status (disregard of status) atau lebih tepatnya menjauhi diskusi kritis tentang status. Ruang publik tidaklah memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas Yang berkuasa, tetapi adanya kesempatan yang Sama dalam mengungkapkan atau mengkritisi sebuah realitas. Bukan pula upaya untuk menciptakan publik yang setara di kafe, salon, atau di antara anggota perkumpulan. Ruang Publik lebih menekankan adanya ide-ide yang terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif sehingga bisa diterima oleh publik secara luas yang jika tidak terealisasikan, minimal ide tersebut melekat secara sadar di benak publik.
Kriteria kedua adalah fokus pada domain of Common concern. Bahwa realitas historis menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penafsirannya oleh otoritas yang berkuasa dan atau oleh kalangan gereja. Padahal domain tersebut bisa dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas. Filsafat, seni, dan sastra yang diklaim hanya boleh diinterpretasikan dan menjadi kewenangan eksklusif dalam hal publisitas oleh kalangan gerejawi, menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh publik. Karya-karya tersebut bukan lagi berada dalam kebutuhan untuk bisa diakses, melainkan sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh industri. Distribusi karya-karya tersebutlah yang menjadi bahan dalam diskusi kritis yang terjadi di ruang Publik. Interpretasi menjadi lebih beragam dan bisa berasal dari siapa saja dalam anggota ruang publik tersebut.
Kriteria terakhir adalah inklusif (inclusivity). Bahwa betapapun eksklusifnya publik dalam kasus tertentu, akan tetapi dalam ruang publik ia menjadi bagian dari kelompok kecil tersebut. Ide-ide yang muncul dalam perdebatan khusus mereka pada dasarnya bukan menjadi milik mutlak anggota ruang publik, melainkan ketika disebarkan melalui media publik dapat pula mengaksesnya. Isu-isu yang diangkat sebagai bahan diskusi menjadi lebih umum, karena setiap orang bisa mengakses sumber-sumber yang terkait dengan isu tersebut. Setiap orang pada dasarnya di ruang publik itu menemukan dirinya bukan sebagai publik itu sendiri, melainkan seolah-olah menjadi juru bicara, dan bahkan mungkin sebagai guru dari apa yang dikatakan sebagai publik itu sendiri yang menurut Habermas sebagai perwakilan atau bentuk baru representasi borjuis.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang publik Habermas merupakan ruang yang Bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara Rasional maupun kritis, dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah-masalah politik. walau karya Habermas memfokuskan diri pada ruang publik dari masyarakat borjuis, namun melalui batu loncatan itulah ruang publik bisa dipahami sebagai ruang yang menyediakan dan melibatkan publik secara lebih luas dalam mendiskusikan realitas yang ada.
Pada era modern sekarang media sosial menjadi wujud nyata sebagai bentuk teori Habermas yang telah dijelaskan diatas tentang teori ruang publik. Dimana media sosial dapat menjadi sarana nyata masyarakat untuk menyatakan opini dalam ruang publik. Media sosial idealnya bersifat independen dari kekuasan pemerintah maupun pasar, sehingga melalui itu masyarakat dapat mempublikasikan aspirasi dan opini mereka untuk tujuan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
Media sosial di Indonesia memang memberikan wujud ideal dari teori Habernas yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai ruang diskusi terbuka di mana semua orang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi memberikan pendapat di media sosial, diskusi rasional fokus terhadap argumen yang kuat dan membangun pemikiran kritis melalui media sosial serta dapat membentuk opini-opini publik. Adanya kemajuan dan kemudahan tentu dimanfaatkan masyarakat dalam menggunakan sosial media seperti facebook, X, youtube hingga instagram. Pengguna internet di Indonesia sebagian besar menggunakan media sosial dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan internet. Kemajuan ini yang mengantarkan sosmed sebagai pilihan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, opini publik, hingga berita yang tak dapat dipertanggung jawabkan (hoax). Tentu dirasa masyarakat bahwa pengoperasian sosmed efisien maka situs-situs website atau aplikasi yang telah dibuat pemerintah terkesan minim diminati masyarakat untuk menyampaikan sesuatu. Masyarakat dalam hal ini diharapkan mampu mengoptimalkan media sosial sebagai alat kontrol sosial, dengan kata lain masyarakat dapat lebih arif dan bijak menggunakan media sosial. Sehingga masyarakat tidak terjebak dengan perilaku maupun perbuatan yang cenderung merugikan dirinya sendiri di kemudian hari.
Sumber:Statista
Jumlah pengguna media sosial di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2024 dan 2029 dengan total 46,7 juta pengguna (+21,87 persen). Setelah sembilan tahun peningkatan berturut-turut, basis pengguna media sosial diperkirakan mencapai 260,23 juta pengguna dan karenanya mencapai puncak baru pada tahun 2029. Khususnya, jumlah pengguna media sosial terus meningkat selama beberapa tahun terakhir.
Angka-angka yang ditampilkan mengenai pengguna media sosial telah diturunkan dari data survei yang telah diproses untuk memperkirakan demografi yang hilang. Data yang ditampilkan adalah kutipan dari Indikator Pasar Utama (KMI) Statista. KMI adalah kumpulan indikator primer dan sekunder pada lingkungan ekonomi makro, demografi, dan teknologi di hingga 150 negara dan wilayah di seluruh dunia. Semua indikator bersumber dari kantor statistik internasional dan nasional, asosiasi perdagangan, dan pers perdagangan dan diproses untuk menghasilkan set data yang sebanding (lihat catatan tambahan di bawah detail untuk informasi lebih lanjut).
Sumber:X
Contoh diatas adalah platform X sebagai forum online, X menjadi panggung bagi beragam suara untuk saling bertukar pikiran dan gagasan. Melalui postingan dan kolom komentar, pengguna dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai topik, mulai dari isu sosial hingga perkembangan terkini.
Namun, media sosial juga dapat menimbulkan polarisasi, konflik, intoleransi, dan radikalisasi di tengah masyarakat. Media sosial juga dapat mengekspos masyarakat kepada filter bubble dan echo chamber, yaitu kondisi di mana masyarakat hanya mendapatkan informasi yang sesuai dengan preferensi atau pandangan mereka sendiri, sehingga mengurangi keragaman dan kritisisme. Beberapa penelitian telah menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi opini publik di berbagai bidang. Misalnya, penelitian Fauzi Syarief (2017) mengkaji bagaimana media sosial Twitter digunakan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membentuk opini publik mengenai berbagai isu politik dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana untuk melihat bagaimana bentuk kalimat, tata bahasa, semantik, dan kosa kata yang digunakan oleh SBY dalam akun Twitternya, sehingga dapat menimbulkan opini publik tertentu. Berikut data pengaruh media social terhadap polarisasi politik.
Sumber: databoks
Kemudian, media sosial di Indonesia juga sering menjadi platform penyebaran berita hoax karena sifatnya yang cepat dan luas dalam menjangkau audiens. Kemudahan berbagi informasi tanpa filter atau verifikasi membuat hoaks dengan cepat menyebar dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten berdasarkan popularitas dan interaksi, bukan validitas, memperburuk situasi ini. Banyak pengguna cenderung lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan pandangan atau emosi mereka, tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Minimnya literasi digital dan budaya cek fakta di masyarakat turut memperparah penyebaran berita palsu di media sosial. Berikut data terkait penyebaran berita hoaks di Indonesia.
Sumber:Databoks
Media social telah menjadi platform dengan berbagai informasi yang sangat cepat di temukan dalam era digital saat ini, polarisasi dan misinformasi di media sosial menjadi tantangan serius bagi masyarakat. Menurut sebuah penelitian oleh Pew Research Center, 64% pengguna media sosial Amerika mengatakan bahwa berita palsu telah menyebabkan “banyak kebingungan” tentang dasar fakta peristiwa-peristiwa dasar dengan situasi ini akan menggambarkan bagaimana peran media sosial dalam penyebaran informasi bisa menjadi hal yang baik dan buruk secara bersamaan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memberikan pendidikan media agar masyarakat dapat mengenali informasi yang valid dan tidak valid. Mengajarkan cara mengecek fakta serta memahami sumber informasi sangat krusial. Selain itu, platform media sosial perlu meningkatkan transparansi algoritma mereka, sehingga pengguna dapat lebih kritis terhadap konten yang mereka terima. Kampanye kesadaran tentang bahaya misinformasi juga dapat membantu, dengan mengingatkan masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kolaborasi dengan ahli dan organisasi terpercaya dapat meningkatkan akurasi informasi yang beredar, sementara dialog terbuka antar kelompok dengan pandangan berbeda dapat mengurangi polarisasi, dan perlunya tindakan tegas terhadap penyebaran informasi palsu, seperti menandai atau menghapus konten yang menyesatkan, sangat diperlukan. Dengan hal ini, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat dan informatif, serta mengurangi dampak negatif dari polarisasi dan misinformasi.
DAFTAR PUSTAKA
Habermas, Jürgen. “Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research”. Communication Theory 16 (2006): 411–426.
Habermas, Jürgen. “The Public Sphere: An Encyclopedia Article. Critical Theory and Society. A Reader. Stephen E. Bronner & Douglas Kellner (Eds.). New York: Routledge, 1989: 136-142.
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1991.
Setiawan, F. R. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. Melintas, 39(3), 323–350. https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826
Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 3(1), 30–43. https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182
Syarief, F. (2017). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik. Jurnal Komunikasi, 8(3), 262–266.
Muhamad, N. (2024). Ada 12.547 Konten Hoaks Selama 5 Tahun Terakhir, Terbanyak Isu Kesehatan. Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/78151e2624ead29/ada-12547-konten-hoaks-selama-5-tahun-terakhir-terbanyak-isu-kesehatan
Dias Maulana Pramudita. (2023). Polarisasi Media Sosial: Membentuk atau Membunuh Dialog Publik? Kumparan.Com. https://kumparan.com/kumparandias/polarisasi-media-sosial-membentuk-atau-membunuh-dialog-publik-20ThWcXcsVA/full
Jayani, D. H. (2019). Media Sosial Meningkatkan Polarisasi Politik di Indonesia. Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/media-sosial-meningkatkan-polarisasi-politik-di-indonesia
Forman-Katz, L. W. N. (2024). Many Americans find value in getting news on social media, but concerns about inaccuracy have risen. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/02/07/many-americans-find-value-in-getting-news-on-social-media-but-concerns-about-inaccuracy-have-risen/
Paggabean, A. D. (2024). Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024. Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024
Qathrunnada, N. (2024). Media Sosial dan Polarisasi Opini Publik: Apa yang Bisa Kita Lakukan? Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/nadyaqathrun/648fb2e84addee41452ed382/media-sosial-dan-polarisasi-opini-publik-apa-yang-bisa-kita-lakukan?page=3&page_images=1