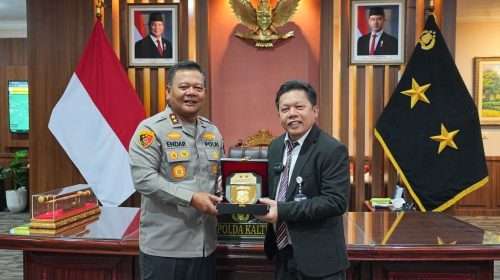Oleh: Imam Syahid, S.I.P., M.Sos
Dosen Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Pendahuluan
Swarakaltim.com – Menjelang akhir 2025, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi pusat perhatian publik. Pemerintah menegaskan bahwa IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta, melainkan simbol transformasi menuju paradigma pembangunan yang merata, hijau, dan berkelanjutan. Namun pertanyaannya, apakah IKN benar-benar mampu menciptakan perubahan struktural, atau justru mengulang logika lama pembangunan yang elitis dan terpusat?
Pembangunan dan Ilusi Transformasi
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan bahwa IKN merupakan “kota masa depan” yang berlandaskan inovasi, keberlanjutan, dan teknologi digital. Namun, bila dilihat dari struktur kebijakan dan praktiknya, logika pembangunan yang dominan masih bertumpu pada pendekatan fisik dan investasi besar.
Hal ini menggambarkan apa yang disebut Anthony Giddens (1984) dalam The Constitution of Society sebagai reproduksi struktur, yakni kecenderungan sistem sosial untuk mempertahankan pola lama meski dalam bentuk baru. Narasi pembangunan hijau sering kali berhenti di tataran simbolik, sementara proyek di lapangan tetap mengandalkan ekspansi infrastruktur masif.
Jalan, perumahan, dan kawasan bisnis menjadi ukuran utama keberhasilan, bukan peningkatan kualitas sosial dan partisipasi warga lokal. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan menjadi transformasi struktural justru berisiko menjadi duplikasi spasial dari sentralisasi lama.
Ketimpangan dan Ruang yang Dikonversi
David Harvey (2002) dalam Spaces of Capital memperkenalkan konsep spatial fix, yaitu strategi negara kapitalis untuk mengatasi tekanan ekonomi dengan membuka ruang geografis baru bagi akumulasi modal. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, pembangunan IKN dapat dibaca sebagai strategi politik-ekonomi untuk mengalihkan tekanan pembangunan dari Pulau Jawa menuju Kalimantan.
Namun tanpa desain tata kelola yang adil, strategi ini berpotensi melahirkan ketimpangan baru. Wilayah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara kini menghadapi tekanan sosial-ekonomi akibat lonjakan harga tanah, migrasi tenaga kerja, serta perubahan tata ruang yang cepat.
Sementara itu, masyarakat lokal dan komunitas adat menghadapi ketidakpastian atas lahan dan akses terhadap sumber daya alam. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif, pembangunan ini justru memperkuat struktur ketimpangan antara pusat dan pinggiran.
Sentralisasi Baru di Atas Otonomi Daerah
Secara administratif, IKN berada di bawah Otorita IKN yang memiliki kewenangan langsung di bawah Presiden. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan otonomi daerah di Kalimantan Timur. Sejak diberlakukannya desentralisasi pasca-1999, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Namun dalam proyek IKN, peran tersebut tampak tereduksi.
Dalam perspektif teori state simplifications yang dikemukakan James Scott (1998) dalam Seeing Like a State, negara sering kali menyederhanakan keragaman sosial dan ekologi lokal demi memudahkan kontrol dan perencanaan. Otorita IKN, dengan struktur birokrasi yang terpusat, berpotensi menempatkan daerah di posisi subordinat terhadap kebijakan pusat.
Kewenangan daerah dalam mengatur tata ruang, perizinan, dan pemberdayaan masyarakat bisa terpinggirkan oleh logika efisiensi yang seragam. Bagi Kalimantan Timur, ini menjadi paradoks: di satu sisi menjadi simbol kemajuan nasional, namun di sisi lain ruang politik lokal justru menyempit. Kaltim berisiko menjadi “ruang administratif” tanpa otonomi substantif dalam menentukan arah pembangunan.
Dimensi Sosial dan Lingkungan yang Kerap Terpinggirkan
Kalimantan Timur bukan ruang kosong. Ia memiliki sejarah sosial, budaya, dan ekologis yang kompleks. Di balik klaim kota hijau, pembangunan IKN menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat Paser dan Balik yang wilayahnya bersinggungan dengan proyek tersebut.
Studi-studi lokal menunjukkan potensi hilangnya ruang hidup tradisional serta tergesernya nilai sosial komunitas. Selain itu, konversi lahan untuk kawasan pembangunan dan fasilitas baru dapat menekan fungsi ekologis hutan penyangga.
Pembangunan yang tidak sensitif terhadap konteks lokal akan mengulang pola eksklusi ekologis, di mana keberlanjutan hanya menjadi jargon kebijakan. Seperti diingatkan Arturo Escobar (2011) dalam Encountering Development, pembangunan sering kali menjadi instrumen dominasi kultural dan ekologis jika tidak disertai refleksi kritis terhadap konteks lokal.
Momentum untuk Menegaskan Demokrasi Lokal
Meski sarat kritik, IKN juga membuka peluang baru. Kalimantan Timur kini memiliki momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha lokal. Dengan pendekatan co-governance sebagaimana dijelaskan Ansell & Gash (2008) dalam Collaborative Governance in Theory and Practice, pembangunan dapat diarahkan pada model partisipatif di mana warga bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan turut menentukan masa depan ruang hidupnya.
Perguruan tinggi di Kaltim dapat memainkan peran sebagai produsen pengetahuan dan pengawas kebijakan publik. Pemerintah daerah pun perlu menegosiasikan ruang partisipasi lebih besar dalam kerangka tata kelola nasional. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi menjadi katalis pembaruan tata kelola yang demokratis dan inklusif.
Penutup
Pembangunan IKN adalah proyek besar yang tidak hanya akan mengubah lanskap fisik Kalimantan Timur, tetapi juga struktur politik dan sosial Indonesia. Tantangannya bukan sekadar membangun kota modern, melainkan menjadikannya ruang demokratis yang adil bagi semua pihak. Jika IKN ingin disebut sebagai transformasi pembangunan, maka transformasi itu harus dimulai dari cara negara mendengar, menghormati, dan melibatkan masyarakat yang menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.(*)
Daftar Pustaka
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Escobar, A. (2011). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.
Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Univ of California Press.
Harvey, D. (2002). Spaces of Capital: Towards a Critical Geography. Routledge.
Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq3vk